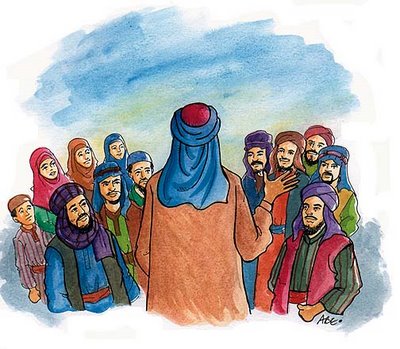
Oleh Prof. Dr. H. Asep Usman Ismail MA
Penegasan Al-Qur`an tentang kewajiban kaum
Muslimin untuk mentaati ûlî al-amr atau pejabat pemerintah sebanding
lurus dengan penegasan Al-Qur`an tentang kewajiban pejabat pemerintah untuk
menunaikan amanat yang dibebankan kepada pundak mereka. Kaum Muslimin tidak
wajib mentaati ûlî al-amr yang tidak mentaati Allah dan tidak menunaikan
amanat yang dibebankan kepadanya untuk melayani rakyat. Pejabat publik yang
tidak amanah kehilangan legitimasi moral, kehormatan dan martabatnya sebagai ûlî
al-amr. Sebab ûlî al-amr diangkat untuk melayani masyarakat luas
pada bidang yang menjadi kompetensinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing institusi yang diatur di dalam administrasi publik. Perhatikanlah
dua ayat Al-Qur`an yang berikut:
”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di
antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah
sebaik-baik yang memberi peringatan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar,
Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika
kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah
(Al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
(Q.S. al-Nisa`/4: 58-59).
Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam
kedua ayat di atas adalah: (1) perintah menunaikan amanat, (2) perintah berlaku
adil dalam menetapkan hukum, (3) perintah taat kepada Allah, Rasulullah,
dan ûlî al-amr dan (4) perintah menyelesaikan perselisihan dengan
mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan materi seperti ini, para
ulama memandang bahwa kedua ayat Al-Qur`an di atas sebagai pokok hukum yang
menghimpun segala ajaran agama.
Nilai essensial yang menjadi pesan utama Surah
an-Nisâ` ayat 58 di atas adalah keharusan setiap orang untuk menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya.
Makna amanat yang paling luas ditemukan dalam
rumusan yang diberikan oleh Thanthawi Jauhari (1287-1358 H), yaitu segala yang
dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan, atau
segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain.
Thanthawi merumuskan amanat secara umum, yakni
menjadikan konsep tersebut lebih abstrak karena rumusan yang dikemukakannya
tidak saja berdasarkan pertanggungjawaban tetapi juga kegunaan yang terkandung
di dalamnya.
Seperti telah dikemukakan, kata amânât
berasal dari kata kerja amina, ya’manu ”merasa aman, memberikan
kepercayaan.” Kata ini dipergunakan dalam Surah Yusuf ayat 11 dan 64. Dalam
ayat pertama dikemukakan riwayat dari saudara-saudara Yusuf mempertanyakan
sikap ayah mereka, mengapa ia tidak mempercayai mereka membawa Yusuf
bermain-main ke tempat penggembalaan. Dalam ayat kedua, dikemukakan penegasan
Yakub yang tidak mempercayakan adik Yusuf kepada mereka karena mereka
menyia-nyiakan kepercayaan yang pernah diberikan untuk menjaga Yusuf. Dalam
ayat yang lain kata amanat dipergunakan dengan konotasi
material. Ini terlihat dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang mengatur masalah
titipan dan pesanan.
Pola lain yang bersumber dari kata amanat adalah
kata amin. Pola ini mengandung konotasi sifat sebagai subyek atau
obyek. Dalam hal pertama, kata tersebut bermakna “yang memberikan rasa aman”
dan dalam hal kedua, kata tersebut bermakna “yang diberi amanat”. Dalam konteks
dengan amanat, maka pola inilah yang pertama kali dipergunakan dalam Al-Qur’an,
yakni dalam surah Al-A’raf, ayat 68 sebagai berikut:
Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan
aku pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu (Q.S. Al-A’raf/7: 68).
Ibnu Kasir mengemukakan bahwa ayat ini menyatakan
sifat-sifat utusan Tuhan, yaitu: menyampaikan seruan Tuhan, memberi nasihat,
dan kepercayaan. Sifat kepercayaan dari para rasul ditemukan pula dalam Q.S.
Al-Syu’ara’, 26/47:107, 125,143,162 dan 178. Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa
para rasul diberi kepercayaan, dan kepercayaan yang dimaksud adalah risalah
atau agama Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia.
Pada Surah Al-Anfal ayat 27 ditemukan penggunaan
kata amanat yang disandarkan kepada manusia. Ayat ini melarang
orang-orang beriman mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkhianati amanat
sesama mereka. Hal ini berarti adanya dua jenis amanat, yaitu: (1) amanat Tuhan
dan Rasul-Nya berupa aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama yang harus
dilaksanakan, dan (2) amanat manusia berupa sesuatu, material atau immaterial
tertentu yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan
ajaran agama.
Bertolak dari konsep amanat di atas, maka
perintah yang terkandung di dalam Surah Al-Nisa ayat 58 di atas mengandung
makna kewajiban menyampaikan amanat, bahwa setiap orang beriman agar menunaikan
amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat dari Allah maupun amanat dari
sesama manusia. Pada sisi lain, sesuai dengan sebab turunnya ayat, penggalan
ayat tersebut mengandung makna khusus, yaitu kewajjiban para pejabat pemerintah
sebagai pejabat publik untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka.
Dari sini dapat dikatakan bahwa ayat di atas memperkenalkan prinsip pertanggung
jawaban kekuasaan politik. Prinsip ini bermakna bahwa setiap pribadi yang
mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar
melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan bahwa kelalaian terhadap
kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri dan juga
bagi kepentingan orang banyak.
Tanggung jawab Ûlîl Amri dalam layanan
publik, menurut Al-Qur`an, merupakan kelanjutan dari tanggung jawab Rasulullah
SAW dalam membimbing umat. Rasulullah SAW selama sepuluh tahun di
Madinah adalah pemimpin agama sekaligus kepala negara. Para ulama mewarisi Nabi
dalam kepemimpinan agama, sedangkan Ûlîl Amri, pejabat
pemerintah yang beragama Islam mewarisi
Rasulullah dalam kepemimpinan negara. Keduanya menyatu secara integral pada
diri Rasulullah, tetapi terpisah pada diri umat beliau di akhir zaman.
Kepemimpinan politik dan kepemimpinan agama idelanya tetap menyatu pada diri
seorang Muslim di akhir zaman, namun faktanya kedua kepemimpinan tersebut
berada pada dua pribadi Muslim yang berbeda, bahkan pada dua lembaga yang
berbeda, yakni pada lembaga ulama dan lembaga umarâ` atau Ûlîl Amri,
namun secara simbiotik keduanya saling melengkapi, saling membutuhkan dan
saling bekerja sama. Umara membutuhkan legitimasi ulama, sementara ulama
membutuhkan dukungan umara untuk menjalankan amar ma’rûf dan nahyi munkar,
memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari
perbuatan keji yang ditolak oleh akal budi dan hati nurani.
Menurut riwayat Hisyam bin ‘Urwah dari Abu Saleh
dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah shallâllâh ‘alayhi wasallam)
bersabda: “Akan datang kepada kamu setelahku para pemimpin. Mereka yang baik
akan memimpin kamu dengan kebaikannya, sedangkan para pemimpin yang jahat akan
memimpin kamu dengan kejahatannya. Dengarkan dan taatilah mereka dalam segala
hal yang sejalan dengan kebenaran. Jika para pemimpin itu berbuat kebajikan,
maka kebajikan itu untuk kamu dan untuk mereka. Demikian juga, jika para pemimpin
itu berbuat kejahatan, maka kejahatan mereka kembali kepada kamu dan menjadi
tanggung jawab mereka (di hadapan Allah).
* Penulis adalah Dewan Pakar Pusat Kajian
al-Quran

Tidak ada komentar:
Posting Komentar